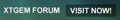Belum Ada Judul (Cerpen Puja)
Embun pertama jatuh. Malam gelap semakin naik. Seusai merampungkan naskah reportase, Darmono berlanjut asyik mengenang masa lalu. Dari dalam kamar kontrakannya yang sempit, terbayang amat lebar seluruh rekaman hidup di benaknya. Banyak indah dan tak jarang pula yang tengil. Bermain bersama teman masa kecil, berjamaah menunggangi kerbau dungu milik Pak Abu, bertengkar dan adu gebuk, bermain petak umpet saat bulan purnama sepulang dari surau, mandi di kali, sampai nyolong mangga kueni di kebun orang untuk kemudian terbirit-birit demi melihat pemiliknya menyalak dengan parang di tangannya.
"Mangga dengan pemilik tipe kikir begini memang wajib dicuri!" Hasut Gendon si kepala rombongan yang kemudian ramai-ramai mereka amini saat itu.
Sesuatu yang meskipun menyedihkan terkadang memang sanggup berubah indah ketika ia telah benar-benar sekadar menjadi untuk dikenang. Semua terbayang amat terang. Lebih terang-benderang katimbang nyala lampu kamarnya malam ini yang sudah mulai bosan bercahaya.
Malam terus terkerek menuju larut. Komputer butut yang selalu berjasa dalam mengerjakan tugas kuliah maupun menulis naskah sebagai jurnalis lepas ia matikan. Darmono membenamkan kepalanya di bantal. Menatap langit-langit kamar. Terlintas kembali satu per satu wajah teman-teman semasa kecilnya. Dari yang paling berani sampai yang paling cengeng. Dari yang besar sampai yang paling ceking. Dari sekian daftar anggota gerombolan, Darmono adalah salah satu dari dua anak yang bertubuh paling kering dan kecil pula di antara mereka. Dan selain pihak terkecil, mereka berdua adalah pihak yang selalu jauh tertinggal di belakang saat ramai-ramai melarikan diri dari acungan golok pemilik mangga yang mereka kemplang. Darmono tersenyum. Indah, manis, asin, geli. "Oo, bahkan sebagai pihak yang kalah pun bukan suatu penghalang untuk menjadi indah saat di kenang." Ah, dimana mereka sekarang?
Lamunannya terus bergulir. Satu satu wajah datang, satu satu ia pergi. Dan lamunan itu harus berhenti lama-lama ketika giliran wajah Ibunya yang bermata teduh penuh kasih muncul. Mata yang selalu ia rindukan. Mata yang meskipun hampir tiap sore hari melotot sambil tangannya membawa ranting pohon, menggiring Darmono kecil yang menjelang senja tak juga berhenti bermain bola plastik di jalanan, namun ia tetaplah mata yang damai. Mata yang selalu dirindukannya. "Wahai, sedang apa ibu di kampung sana? Tidur lelap barangkali. Memimpikan aku semoga."
"Dar, aku pamit. Nanti sore aku pulang kampung. Mohon maaf lahir batin ya.." Ucap Sofi teman sekelasnya seusai perkuliahan ditutup.
"Iya, sama-sama Fi, semoga selamat sampai rumah." Jawab Darmono tak lupa dengan senyum khasnya.
"Makasih. Kamu kapan pulang? Tujuh hari lagi udah lebaran lho.." Tambah Sofi sembari membalas senyum.
"Belum jelas kapan kepulanganku tak mengapa. Asalkan bedug magrib nanti jelas dan tak diundur-undur." Sahut Darmono sambil lalu. Sofi tak bisa untuk tak tergelak.
Sofi lama menaruh hati pada Darmono tapi ia menyembunyikannya. Baginya adalah pantangan besar perempuan lebih dahulu mengungkapkan perasaan kepada lelaki. Pantangan di benak Sofi itu serupa dengan pantangnya kelapa muda yang masih erat di pohonnya. Ia tidak boleh sekonyong-konyong jatuh. Harus ada yang memetiknya terlebih dahulu. Prinsip yang entah datangnya dari mana namun ini dipegang erat oleh Sofi. Erat, yakin, meski terkadang juga ragu. Ragu tapi yakin. "Ah, dasar keturunan Jowo. Lek gak begitu yo mbalelo!" batin Darmono geli. Maka tingkah Sofi yang sedikit sudah berani menyapa saja adalah suatu kemajuan besar yang patut dipuji, diberi hadiah kalau perlu. Tapi betapa kemajuan yang seperti itu nyaris sia-sia belaka. "Darmono memang batu! Primitif!" Maki Sofi, cuma di hati.
Darmono bukan tak tahu, ia juga bukan buta kalau Sofi memang cantik. Bohong kalau laki-laki tak pernah berdesir jantungnya melihat Sofi yang manis. Tapi, Darmono cuma hendak menjadi diri sendiri. Diri sendiri yang meskipun tampangnya sembarangan tapi ia lebih memilih untuk nekat cuek. Dan celakanya kenekatannya untuk cuek itulah yang secara ajaib justeru malah membuat gadis secantik Sofi jatuh kecantol. "Wanita memang bisa cantik. Ia juga menjadikan hidup ini berubah jadi cantik. Tapi cantik akan jadi petaka kalau belum siap waktunya." Batin Darmono ngeyel.
***
Darmono duduk di bangku menikmati es tebu sebagai minuman berbuka puasanya. Memburu berita tentang demo di jalan protokol yang menuntut pengulangan pemilihan wali kota membuatnya harus berbuka puasa di jalan. Sepeda motornya yang lamban tak kuasa jika harus mengejar waktu agar bisa berbuka di kontrakan. Inilah resiko bekerja sebagai jurnalis. Ya, tak ada cabang hidup yang tanpa resiko. Bahkan tiga hari sebelum lebaran saja masih sempat demo! Merepotkan. Tak apa, demi pekerjaan. Pekerjaan yang ia lakukan bukan cuma karena kesempitan hidupnya, terlebih ia memang mencintainya. Kesempitan memang tak enak dan menyebabkan aneka keterpaksaan. Terpaksa bekerja, terpaksa lapar, terpaksa gemetar. Namun hidupnya memang sudah kepalang kuyup dengan kesempitan. Maka, ia memutuskan untuk bersahabat sekalian dengan kesempitan. "Hidup yang separo sudah berisi kesempitan, jangan ditambah dengan separo lagi kesedihan. Muka pasti tambah jelek."
Waktu untuk Darmono kembali ke kampung datang. Kini ia sedang berdiri di muka rumah. Rumah sederhana. Betapapun sederhana, ia tetaplah lebih membuat Darmono rindu katimbang hotel mewah sekalipun. Bukan soal mewahnya, tetapi penghuninya. Didalamnya berisi Ayah, Ibu dan adik-adiknya yang pasti mencintai dan dicintainya. Komplit. Dipandangnya lekat-lekat rumah papan itu. Tak banyak berubah semenjak satu tahun kepergiannya. Sederhana tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan sejuta keindahan.
Ibu Darmono membuka pintu demi mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Matanya berbinar. Senyumnya terkembang. Berbinar melihat anak sulungnya kembali. Betapapun ia anakku. Sayang sekali kalau lebaran sampai tak pulang. Tersenyum mendapati penampilan Darmono yang masih sama desa-nya. Yang ini wajib diberi senyum. Tak sedikit anak desa ini yang begitu kenal dengan gaya anak muda kota terus latah ikut-ikutan. Mulai rambut yang lancip berdiri, yang seperti Ultraman! Sampai yang dicat merah, pakai tindik tak cukup cuma di telinga, celana melorot, bolong di lutut pula. "Puih! Itukah anak kota?" Yang terang, populer itu terkadang memang mudah diikuti tak peduli walaupun terlihat aneh. Urakan malah.
"Bu, apakabar desa ini?" tanya Darmono sambil mencabuti rumput di halaman rumah pada esok paginya.
"Ya, baik-baik aja Dar. Masih seperti biasa. Yang jelas tidak gemrungsung seperti di kotamu itu." Jawab Ibunya datar. Darmono nyengir.
"Ya maksudnya.. Ada yang mati nggak Bu?" Tambah Darmono lagi. Ibu melotot. Anak sulungnya selain tetap desa ternyata tetap urakan pula gaya bicaranya.
"Koe..! Nggak ada.." Darmono tergelak.
"O iya, Si Amin itu udah pulang belum Bu?" Tanya Darmono lagi sopan.
"Belum. Sudah tiga tahun. Kata emaknya sih dia kerja di Irian sekarang. Di tambang emas. Di PT. Repoot apa apalah itu namanya."
"Oo.. " Gumam Darmono datar.
"Byuh! Cari duit kok ya nggak tanggung-tanggung. Irian!" Pekik Darmono. Cuma di hati tapi. Sebegitu sulitkah cari hidup? Ya, nyatanya bisa saja. Di kampungnya yang berhamburan kebun sawit pun masih ada saja yang kekurangan. Kalau yang tidak punya kebun dan merasa kekurangan itu wajar saja. Tapi Darmono mengerutkan dahi demi mendapati betapa orang yang punya berpuluh hektar kebun sawit toh masih ada yang merasa kurang juga. Amboi!
Masa silam bersama Amin teman kecilnya lalu berhamburan. Bermunculan satu per satu tak terhitung seperti rumput yang sedang dicabutinya. Betapa Amin adalah sahabat karibnya. Bukan cuma karena dahulu sama-sama kecil dalam gerombolan anak-anak yang tentu menimbulkan rasa kebersamaan. Sama-sama kerempeng. Sama-sama pihak yang selalu kalah. Sama-sama paling buntut dalam berlari. Tapi juga karena mereka kemana-mana selalu bersama. Berdua. Ada Amin, Ada Darmono. Ada Darmono ada Amin.
Keduanya pernah bertengkar. Bertengkar pun cuma karena saling ejek. Ejekan yang kurang bermutu pula.
"Hey, kau pacarnya Tini yang ompong itu kan?" Olok Darmono lalu tertawa besar.
Amin melotot. Betapapun ia tidak imut. Tapi kalau harus disebut punya pacar ompong ia marah juga.
"Alaaah, lha kamu.. Pacarnya Dita yang keriting itu! Wee.." Balas Amin tak mau kalah.
Darmono ganti melotot sebesar bola dunia. Rambutnya lurus. Meski agak merah. Maka dalam benak Darmono kecil, ia merasa boleh anti dengan rambut keriting. "Kayak Supermi!"
"Enak saja! Aku jepret ketapel kamu!" Tantang Darmono.
"Haa, siapa takut sama ketapelmu yang terkutuk itu!" Sambut Amin garang.
Keduanya mendidih. Darmono berani. Amin tidak takut. Mereka saling tubruk dan berguling-guling di tanah, di bawah rindang pohon karet. Berdebum bukan bunyi pukulan tapi bunyi tubuh yang sedang berputar-putar kacau di atas tanah. Meracau sejadi-jadinya. Keduanya berteriak tak jelas. Kalau dilihat malah bukan seperti anak kecil sedang berkelahi. Tapi, sekadar anak yang sedang berpelukan kemudian berguling-guling saja. Darmono geli. Ingin ia menjadi kecil lagi.
"Betapa pernah menjadi anak-anak adalah anugerah." Kenang Darmono. Anugerah karena bisa berkelahi dan esok harinya sudah akrab kembali. Berkelahi yang seperti ini adalah tipe berkelahi yang meski kurang bermutu tapi ia menyenangkan. Menyenangkan karena begitu mudahnya dalam memaafkan. Tak ada dendam. Kalau sudah tak lagi menjadi anak-anak, berkelahi bukan tidak mungkin terjadi. Memaafkan pun mungkin mudah saja diucapkan. Tapi, untuk tidak mendendam sama sekali, adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Dan kalau toh antara Darmono dan Amin kini dipertemukan cuma untuk berkelahi, jelas itu bukan tontonan yang lucu. "Beruntung aku pernah merasakan berkelahi." Batin Darmono tersenyum geli.
Oh, Sobat. Masih ingatkah, kau?
Pekanbaru, 25 August 2011 by Puja K.
Dibaca: 1679